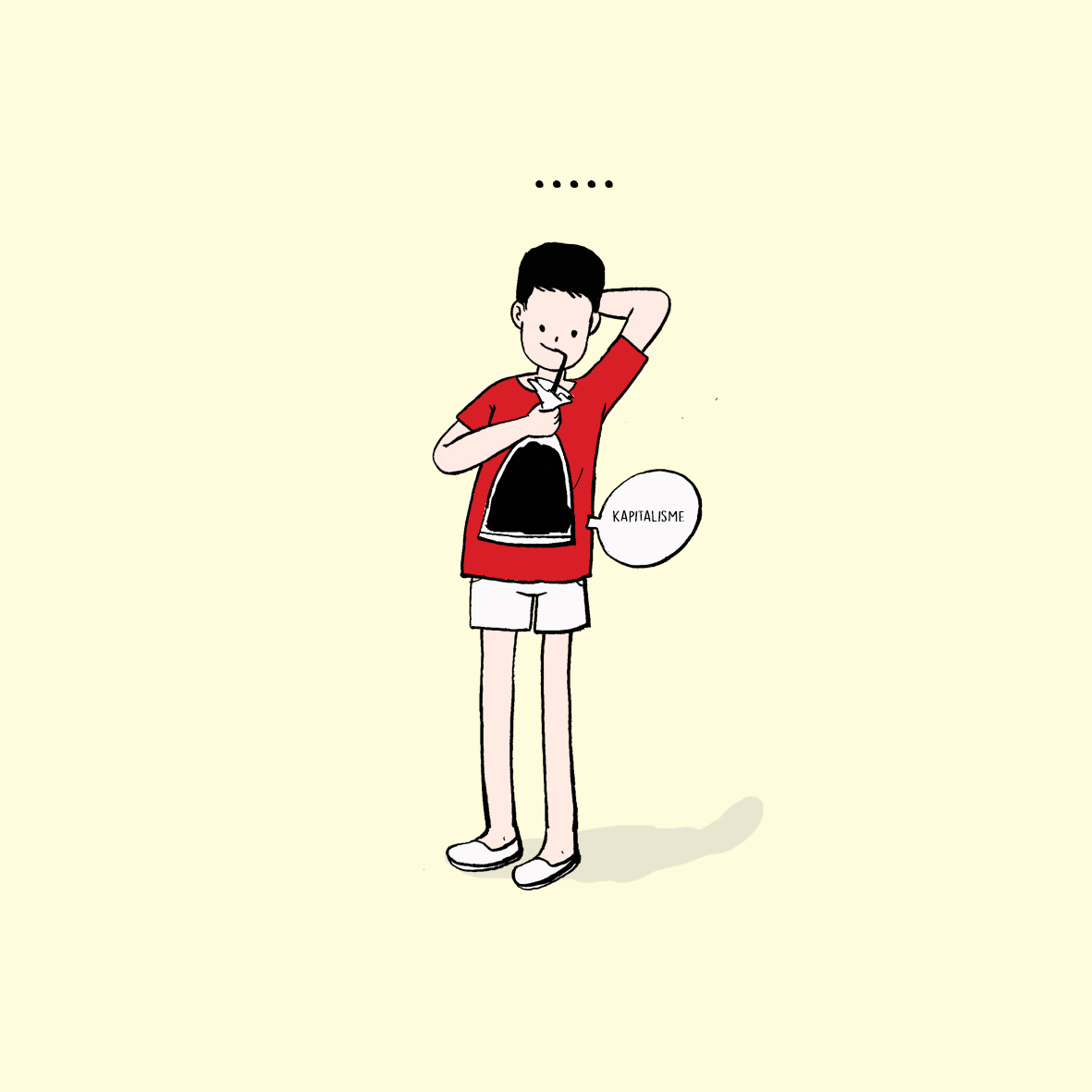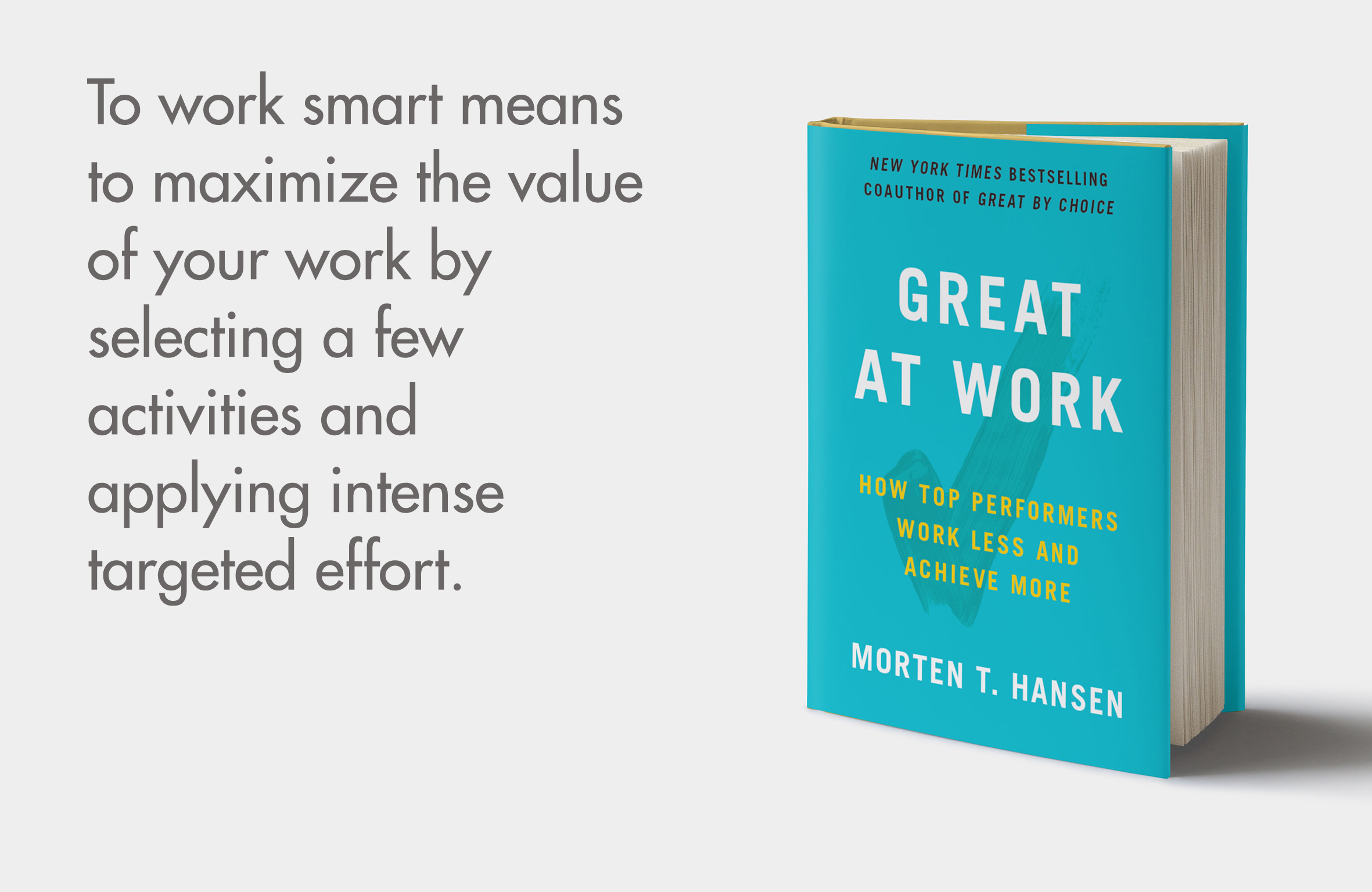“Loh, saya mengajukan naskah untuk diterbitkan, kok malah disuruh beli sendiri?” kata seorang calon penulis. Sepintas ini tampak ganjil, namun dia tidak sendirian. Kasus yang serupa dialami oleh banyak orang ketika mendatangi penerbitan. Apakah Anda juga merasa aneh dengan hal ini?
Mari mendalami latar belakangnya. Penerbitan sebuah buku didahului oleh sebuah perjanjian kerja sama, antara penerbit sebagai pihak pertama dan penulis sebagai pihak kedua. Penerbit memiliki modal berupa dana dan kemampuan distribusi, dan penulis memiliki modal yang tidak kalah besar, yaitu isi atau konten. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing, dan saling membutuhkan.
Penulis membutuhkan penerbit, selayaknya seorang pengembang startup membutuhkan pendana. Alasannya: mencetak buku dan mendistribusikannya di toko-toko buku membutuhkan dana yang tidak sedikit. Semakin besar penerbit tersebut, semakin luas distribusi yang bisa dilakukan, semakin kuat pula jaringan pemasarannya.
Berapa dana yang dibutuhkan? Untuk buku berspesifikasi standar (300 halaman, ukuran 15 x 22 cm), dibutuhkan biaya produksi sebesar 40 jutaan. Biaya produksi tersebut mencakup biaya desain, kertas, dan ongkos cetak, yang harus dibayar di muka. Belum lagi ditambah ongkos lain berupa distribusi, promosi, insentif untuk toko-toko buku, serta pajak, yang menjadi beban administrasi untuk pihak penerbit. Ini menguras kocek penerbit kira-kira hampir 25 jutaan. Penerbit pun masih harus mengatur besaran diskon untuk toko buku serta berbagi keuntungan dengan penulis, dan juga biaya inventory turn over, serta gudang. Singkatnya, satu buku dengan spesifikasi di atas melibatkan struktur keuangan senilai mencapai 140 jutaan.
Angka yang tidak kecil bukan?
Di sisi yang lain, penerbit tentu membutuhkan penulis, terutama penulis yang bisa mencetak penjualan yang besar (baca: bestseller). Sebab, dengan melihat biaya yang segitu besar, sebuah penerbitan tidak mau main-main asal cetak. Itulah mengapa, sebuah penerbit merekrut editor, yang mampu menemukan talenta-talenta kepenulisan yang ciamik, atau figur-figur yang bisa menarik perhatian pembeli. Sebuah naskah yang mungkin hanya berupa berlembar-lembar hvs, di-print di sebuah warnet dan difotokopi di pinggir jalan, tidak bisa begitu saja diremehkan. Di mata seorang editor yang tajam, bisa jadi itu adalah cikal bakal mega bestseller dengan profit milyaran
Proses kerja sama di balik sebuah penerbitan buku memang pada dasarnya sesederhana itu. Pemodal, dalam hal ini penerbit, mengorbitkan penulis. Ia mendanai produksi dan distribusi, dan keuntungannya nanti dibagi. Jika laku keras, mereka sama-sama untung; jika gagal, dari perhitungan di atas, penerbit tentu harus menanggung kerugian atas dana yang telah keluar. Penulis, karena sama sekali tidak mengeluarkan duit, tidak menanggung kerugian apa pun, kecuali bahwa kelak di karya berikutnya, ia harus kerja lebih keras lagi untuk meyakinkan penerbit supaya bisa dicetak.

Jadi, Adakah Pengecualian?
Jika begitu, penerbit yang meminta penulis membeli bukunya sendiri, berarti melakukan penipuan dong? Tunggu dulu.
Logikanya, memang hanya naskah yang benar-benar terseleksi yang bakal didanai oleh penerbit, sebab mana ada, penerbit yang mau rugi. Namun begitu, ada penulis yang “ngebet” bikin buku. Walaupun di mata penerbit, naskah yang diberikan tidak lolos seleksi, mereka tidak memedulikan hal tersebut.
Mengapa demikian? Sebab, mereka memiliki motivasi yang berbeda.
Ada yang menulis buku untuk keperluan branding. Tahukah Anda, sebuah buku masih merupakan alat yang efektif (dan efisien) untuk melegitimasi profesionalitas, ketokohan, dan segala predikat lain. Tidak mengherankan, buku-buku dengan konten biografi tokoh tertentu santer terbit menjelang Pilkada atau Pileg. Selain untuk branding, ada juga yang menulis buku untuk keperluan momen atau event tertentu, misal: persembahan (tribute) ulang tahun tokoh tertentu, seminar, lokakarya, atau referensi perkuliahan.
Buku-buku semacam ini tentunya tidak akan mudah dijual. Tingkat urgensi dan kepentingan yang rendah, tidak cukup mendorong pasar untuk membeli. Segmentasinya juga terbatas.
Di sinilah letak pengecualiannya. Dalam kasus ini, penulis diajak untuk ikut menanggung ongkos penerbitan. Karena penerbit merasa tidak mampu menjual konten tersebut, penulis diminta untuk ikut menanggung pemasarannya. Jadi, penerbit bersedia menerbitkan naskah tersebut asalkan penulis mau mengambil sekian eksemplar dari oplah, untuk ia pasarkan sendiri. Sederhananya, penerbit bersedia menerbitkan naskah tersebut sebesar 5000 eksemplar, asalkan penulis mau membeli 2000 eksemplar untuk dipasarkan sendiri, bisa melalui seminar-seminarnya, komunitasnya, atau event suatu institusi. Dengan demikian, penerbit tidak menanggung risiko yang terlalu besar (atau bahkan mendapatkan keuntungan di awal), karena sudah terjadi pembelian.
Karena penulis membutuhkan buku sebagai branding dan karena baginya, ada keuntungan besar jika naskah itu diterbitkan oleh penerbit tersebut (dianggapnya bisa menaikkan prestise), ia akan menyanggupinya. Kedua pihak sama-sama untung. Penulis mendapatkan branding, penerbit mendapatkan keuntungan. Terjadi kesepakatan, atas pemikiran sama-sama untung.
Inilah yang dinamakan copublishing.

Alternatif Jika Anda Tidak Mau Membeli
Copublishing hanyalah salah satu cara berbisnis sebuah penerbit. Mereka tidak menerapkan pola tersebut pada setiap penulis atau naskah yang datang. Bisa disimpulkan, copublishing adalah sebuah solusi yang mendamaikan kebutuhan 2 pihak.
Jika Anda adalah seorang penulis baru dan disodori alternatif copublishing oleh penerbit, artinya naskah Anda dianggap masih belum sepenuhnya marketable (belum menjual). Namun memandang bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengorganisasi penjualan melalui kanal-kanal atau komunitas yang Anda miliki, penerbit bersedia bekerja sama.
Jika Anda melihat nilai plus dari brand penerbit, yang akan mendongkrak nama Anda, alternatif copublishing sangat patut diambil. Misalnya: Anda sangat ingin novel Anda diterbitkan oleh suatu penerbit mayor, ambillah tawaran itu.
Namun, jika Anda tidak tergantung oleh hal tersebut, dan berniat untuk membuktikan diri, sangat dianjurkan untuk menerbitkannya melalui jalur indie. Anda bisa menerbitkan sendiri buku Anda secara mandiri, dan memasarkan sendiri melalui kanal-kanal yang Anda miliki. Ongkos produksi dan distribusi yang ditanggung sendiri, tentu akan memberikan harga jual yang lebih rendah, sehingga meringankan beban Anda. Jelas tidak akan sebesar biaya kontribusi penulis melalui copublishing.
Atau, alternatif lain selain indie adalah memperbaiki naskah Anda. Sederhananya, belajarlah lagi untuk membuat naskah yang bisa memikat penerbit. Coba dan coba lagi.